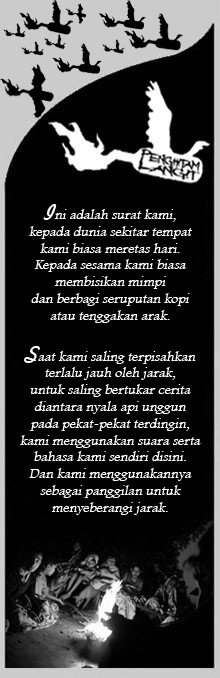Malam ini para pecundang tidur, atau berbaring terbelalak dan melipat tangan: penari yang pincang, pahlawan yang cedera, seniman yang disiakan; mereka mengungsi dari tanah terkoyak, di mana mimpi mati seperti cinta dalam tangan.
Sementara di luar jaman baru itu bocah-bocah tersesat dan iblis bermain tepat di depan rumah kita. Tuhan baru menyatakan sumpahnya menelan bulat-bulat –tanpa mengunyah, membersihkan tanah dari belulang yang menghitam dan menyiapkan sepuluh juta ranjang di neraka. Karena cepat atau lambat kita semua akan datang.
Dalam bising ini, lidah sunyi yang menyiksa, terikat kata yang tak terucap, lagu yang tak pernah disenandungkan. Janji yang lebih sering diabaikan--bukan diingkari, terkunci dalam ruangan yang takkan pernah terbuka. Dan tak seorangpun di bumi ini yang bisa dapatkan apa yang ia mau. Dan itu indah, atau sekedar mendekati.
Kita akan mencengkeram sesal, membungkam yang lainnya, memotong hati dari dada kita dan kita berjalan terus, mata terpejam, sunyi, beriringan menuju tanah yang dijanjikan oleh penipu.
Ketika pendahulumu kehilangan kepalanya atau menjual jiwanya dan melayani ular sebagai dewa, mengukir ulang dunia seperti yang diidamkan, sementara sisanya mengalihkan pandangan, kita akan menyalakan api dalam hati dengan gairah yang takkan pernah bisa terbeli untuk menangkap pagi dari terkaman malam –menculik sang mati dan menghidupkannya.
takadakata
takadasentuhan
takadatidur
takadapercaya
takadaharapan
takadakeyakinan
takadatempatistirahat
Dari kenangan masa kecil dalam buaian orang asing sampai kamar rumah sakit, sel penjara dan pantai yang jauh. Tak berumah, tak berhati, tak tenang, tak berdiri, tak hidup, tak bercinta. Kurang, kurang dan kurang.
Jika pagi datang terlambat kali ini, mentari yang kacau akan terbit untuk mencari jemari yang tercekam erat dalam kulit yang mengelupas oleh mimpi yang dibangun dari debu dan akhirnya mati. Mati di tanah kematian –kau bisa menyebutnya bunuh diri, sebagaimana aku teriak demi secercah fajar. Dan ia datang di semua ufuk, bagai awan mengumpul, menjegal pintu untuk menyumpalnya.
Dekatkan telinga ke hati akan kau dengar, dalam dada sendiri, detak-detak berjalan.
Tutuplah
tak ada yang suci
tak ada yang murni
tak ada yang pasti
tak ada yang bebas
di sini
dan di dunia ini tak ada yang aman
tak ada yang adil
tak ada yang benar di dunia ini
dalam hidup yang bisa kuandalkan
dan pagi pun terlambat menyapa.
Susu asam berwarna hitam yang kita minum bersama roti bakar di suatu senja, dalam kesunyian yang berkumpul ketika malam datang –ketika kita menulis puisi cinta di atas jasad yang kelak mati, mencerna kebanggaan dari bisa dalam menu sehari-hari, membasuh kesadaran dari air mata sang pemerkosa, dan menjejak kenikmatan di pinggiran rasa sakit. Kau pun mengoceh tentang hukum dan hak yang saat ini tak kupercaya, tak kurasa.
Akan kuludahi kembali wajahmu –keturunan terakhir ras iblis. Kita semua iblis di tempat ini. Berikan saja aku sejumput rasa.
(Taufan Ishmael)
Sementara di luar jaman baru itu bocah-bocah tersesat dan iblis bermain tepat di depan rumah kita. Tuhan baru menyatakan sumpahnya menelan bulat-bulat –tanpa mengunyah, membersihkan tanah dari belulang yang menghitam dan menyiapkan sepuluh juta ranjang di neraka. Karena cepat atau lambat kita semua akan datang.
Dalam bising ini, lidah sunyi yang menyiksa, terikat kata yang tak terucap, lagu yang tak pernah disenandungkan. Janji yang lebih sering diabaikan--bukan diingkari, terkunci dalam ruangan yang takkan pernah terbuka. Dan tak seorangpun di bumi ini yang bisa dapatkan apa yang ia mau. Dan itu indah, atau sekedar mendekati.
Kita akan mencengkeram sesal, membungkam yang lainnya, memotong hati dari dada kita dan kita berjalan terus, mata terpejam, sunyi, beriringan menuju tanah yang dijanjikan oleh penipu.
Ketika pendahulumu kehilangan kepalanya atau menjual jiwanya dan melayani ular sebagai dewa, mengukir ulang dunia seperti yang diidamkan, sementara sisanya mengalihkan pandangan, kita akan menyalakan api dalam hati dengan gairah yang takkan pernah bisa terbeli untuk menangkap pagi dari terkaman malam –menculik sang mati dan menghidupkannya.
takadakata
takadasentuhan
takadatidur
takadapercaya
takadaharapan
takadakeyakinan
takadatempatistirahat
Dari kenangan masa kecil dalam buaian orang asing sampai kamar rumah sakit, sel penjara dan pantai yang jauh. Tak berumah, tak berhati, tak tenang, tak berdiri, tak hidup, tak bercinta. Kurang, kurang dan kurang.
Jika pagi datang terlambat kali ini, mentari yang kacau akan terbit untuk mencari jemari yang tercekam erat dalam kulit yang mengelupas oleh mimpi yang dibangun dari debu dan akhirnya mati. Mati di tanah kematian –kau bisa menyebutnya bunuh diri, sebagaimana aku teriak demi secercah fajar. Dan ia datang di semua ufuk, bagai awan mengumpul, menjegal pintu untuk menyumpalnya.
Dekatkan telinga ke hati akan kau dengar, dalam dada sendiri, detak-detak berjalan.
Tutuplah
tak ada yang suci
tak ada yang murni
tak ada yang pasti
tak ada yang bebas
di sini
dan di dunia ini tak ada yang aman
tak ada yang adil
tak ada yang benar di dunia ini
dalam hidup yang bisa kuandalkan
dan pagi pun terlambat menyapa.
Susu asam berwarna hitam yang kita minum bersama roti bakar di suatu senja, dalam kesunyian yang berkumpul ketika malam datang –ketika kita menulis puisi cinta di atas jasad yang kelak mati, mencerna kebanggaan dari bisa dalam menu sehari-hari, membasuh kesadaran dari air mata sang pemerkosa, dan menjejak kenikmatan di pinggiran rasa sakit. Kau pun mengoceh tentang hukum dan hak yang saat ini tak kupercaya, tak kurasa.
Akan kuludahi kembali wajahmu –keturunan terakhir ras iblis. Kita semua iblis di tempat ini. Berikan saja aku sejumput rasa.
(Taufan Ishmael)